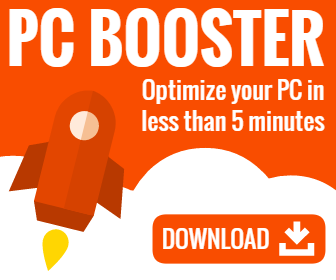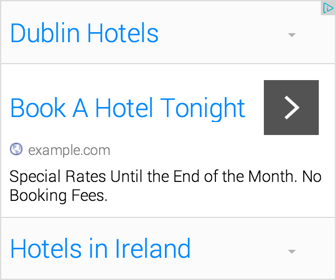Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai penanganan demonstrasi yang belakangan ini malah memperlakukan para demonstran layaknya penjahat dan hal ini juga dapat mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Ketua YLBHI, Asfinawati menilai bahwa penanganan demonstrasi belakangan ini justru mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dia khawatir jika penanganan demo seperti ini terus berlanjut Indonesia akan mengarah pada negara otoriter.
“Penanganan demonstrasi saat ini, Pertama, niatnya untuk menggagalkan atau setidaknya membubarkan demonstrasi. Kedua, memperlakukan orang yang berdemonstrasi sebagai penjahat seolah-olah itu kesalahan atau tindakan terlarang, dibuktikan dengan penangkapan-penangkapan sebelum dan sesudah aksi,” kata Asfinawati kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).
Sejak RUU Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10) lalu, gelombang aksi penolakan Omnibus Law terus menguat. Sehari setelah pengesahan itu, polisi menangkap belasan pelajar yang hendak aksi di DPR RI, Jakarta. Penangkapan jelang aksi itu terus berlanjut hingga sepekan berikutnya.
Pada Sabtu (10/10) lalu, Mabes Polri menyampaikan sedikitnya 5.918 orang ditangkap saat aksi Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Kamis (8/10). Polisi menangkap mereka karena diduga membuat kericuhan. Sebanyak 167 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara pada unjuk rasa 13 Oktober lalu, polisi menangkap 1.377 orang. Sebagian besar sudah dipulangkan dan ada pula yang diproses hukum karena terindikasi melanggar pidana.
Pihak kepolisian juga akan mencatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) para pelajar yang mengikuti demo menolak UU Cipta Kerja dan tertangkap oleh aparat. Mereka terancam sulit untuk melamar pekerjaan karena umumnya pekerjaan memiliki syarat untuk memiliki SKCK.
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti penangkapan sewenang-wenang ini, baik sebelum aksi ataupun setelah aksi. Mereka menilai anggota Polri sering kali melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aksi dengan dalih pengamanan.
Mereka menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan.
“Alasan pengamanan ini merupakan tipu daya polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang,” tulis Koalisi dalam siaran pers, Rabu (14/10).
Polisi sebelumnya menyebut mereka yang diamankan adalah pengunjuk rasa yang terindikasi berbuat rusuh. Ada pula yang membawa benda terlarang seperti senjata tajam.
Mereka yang tidak terindikasi melanggar hukum akan dipulangkan. Sementara jika polisi punya bukti permulaan cukup, pengunjuk rasa tersebut akan diproses hukum.
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) juga menuntut pemerintah dan DPR untuk menghentikan narasi yang menutup ruang dialog dengan mempersoalkan kewajiban membaca naskah undang-undang sebelum berdemonstrasi.
Pernyataan itu merespons gejolak atas gejolak atas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat.
APHTN-HAN meminta pemerintah dan DPR untuk membuka ruang dialog dengan para demonstran guna menemukan jalan keluar terbaik.
“Buka ruang dialog dengan para pemrotes dan segera diskusikan jalan keluar yang baik secara hukum dan politik mengenai situasu ini, termasuk kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan RUU Cipta Kerja ini,” ujar salah seorang perwakilan APHTN-HAN, Bivitri Susanti melalui keterangan resminya, Rabu (14/10).
Bivitri mengatakan bahwa pihaknya menemukan catatan buruk pelanggaran protes legislasi dan pembungkaman hak berpendapat melalui kekerasan dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja.
Terkait proses legislasi, ia mengatakan publik dipertontonkan pelanggaran yang sangat jelas. Dalam hal ini Bivitri mempersoalkan agenda Rapat Paripurna Tingkat II yang semula diagendakan pada 8 Oktober 2020, namun dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020.
Ia juga menyoroti pengesahan RUU tanpa draf final dan tanpa diketahui isinya oleh sejumlah anggota dewan. Belakangan ini diketahui bahwa terdapat 5 draf RUU Cipta Kerja yang beredar ke publik.
“Kita tidak bisa hanya berbicara soal tidak ada teks Pasal yang mengatur bahwa persetujuan mensyaratkan naskah final. Kita berbicara nilai-nilai konstitusional dan cara-cara demokratis,” kata Bivitri.
Sedangkan perihal kekerasan, ia menyinggung kasus yang menimpa anggota APHTN-HAN yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berinisial AM. AM yang bukan bagian dari massa aksi, kata Bivitri, justru mendapat kekerasan fisik dan verbal dari aparat kepolisian hanya karena berada di lingkungan unjuk rasa.
Bivitri menyatakan bahwa penanganan demo dengan kekerasan bukan merupakan pilihan dalam sebuah negara hukum.
“Tugas aparat negara untuk mengelola agar unjuk rasa berlangsung dengan baik. Bila ada pelanggaran hukum, penegakan hukum harus dijalankan dengan konsisten, tidak dengan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan penyiksaan di tempat,” tambahnya.
DPR resmi mengirimkan draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10) kemarin. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyatakan draf UU yang dikirimkan pihaknya berjumlah 812 halaman.
(CNN/ZA)